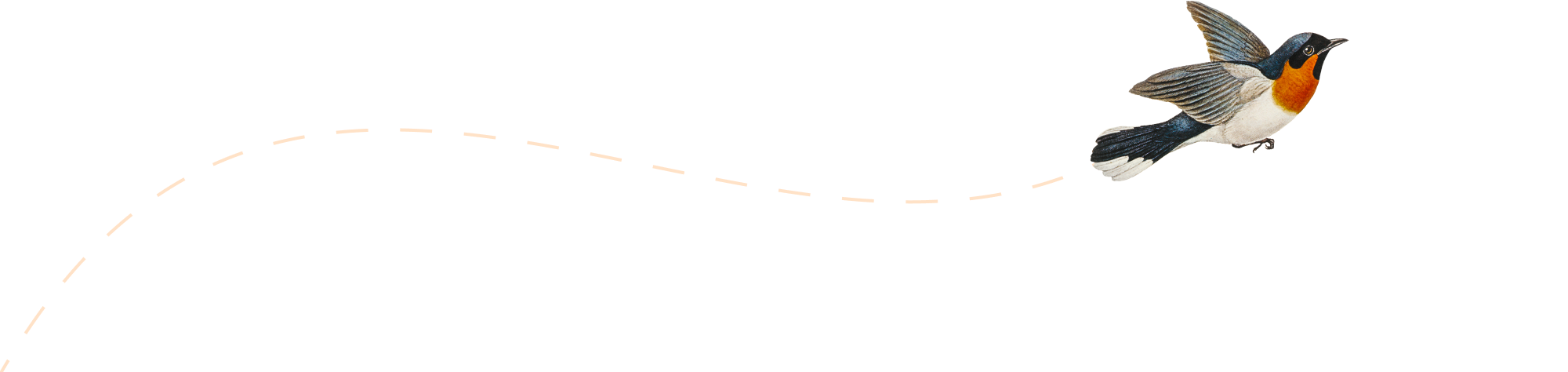-
Panduan Registrasi
Untuk panduan registrasi, unduh disini
-
Panduan Perwalian di Telkom University
Untuk panduan perwalian, unduh disini
-
Activity theory
Teori ini dikembangkan oleh Lev S. Vygotsky, seorang ilmuwan psikologi dari Rusia. Teori ini didasari dari pemikiran marxisme. Pada umumnya manusia membangun aktivitas ideal (simbolisasi) sebelum mengaplikasikannya dalam tindakan (konkret). Aktivitas simbolisasi merujuk pada perencanaan dalam diri individu, seperti “apa yang akan saya katakan dalam percakapan nanti”; atau dapat pula terjadi diluar diri, seperti seorang…
-
Activation theory of information exposure
Teori ini dikembangkan oleh Lewis Donohew dan Philip Palmgreen sejak tahun 1990-an. Teori ini menjelaskan tentang perbedaan individu dalam perhatiannya terhadap pesan antarpribadi dan massa. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan atau kegagalan pesan sebagai sebuah stimuli akan tertahan hingga pendengar/penonton/pembaca tertarik, dimana ketertarikan tersebut didasarkan pada kebutuhan kogntif dan biologis individu tersebut.
-
Action-implicative discourse analysis (AIDA)
Dikembangkan oleh Karen Tracy dan Robert Craig tahun 1990-an. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia mampu menyusun apa yang akan dikomunikasikan untuk tujuan yang diinginkan. Teori ini lebih fokus pada praktik komunikasi yang terjadi dalam sebuah institusi.
-
Action assembly theory (AAT)
Dikembangkan oleh John Greene sejak tahun 1980-an. Menjelaskan proses bagaimana manusia menciptakan pesan verbal dan non-verbal. Mengkaji kondisi kesadaran manusia dalam membangun kreativitas yang menghasilkan pikiran dan tindakan. Teori ini megkaji pula hubungan antara pikiran dan tindakan yang dipertunjukan, hubungan antara komponen verbal dan nonverbal, dan bagaimana orang merencanakan serta mengatur apa yang mereka katakan.
-
Accomodation theory / Communication acomodation theory (CAT)
Dikembangkan sejak 1950-an melalui penelitian-penelitian sosiolinguistik. Teori ini menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana seseorang beradaptasi terhadap komunikasi yang mereka lakukan dalam menghadapi situasi sosial yang berbeda. Teori ini menekankan pada penggunaan bahasa yang digunakan dalam komunikasi, dimana ia akan menyesuaikan derajat formalitas bahasa yang digunakan dalam konteks sosial yang berbeda. Teori ini menjelaskan pula tentang…
-
Skala teori menurut Em. Griffin
Tahukah anda, ada beberapa teori yang objektif, dan ada beberapa teori yang subjektif. Berikut skalanya menurut Em. Griffin: skala-teori-komunikasi-dalam-skala-perspektif-objektif
-
Dicourse menurut Theo Van Leeuwen
Leeuwen mendefinisikan discourse (wacana) sebagai “as socially constructed knowledge of some aspect of reality” [1]. Wacana adalah sumber untuk merepresentasikan sesuatu. Wacana dapat dianggap sebagai pengetahuan tentang realitas. Dimana baru dapat dipahami ketika aspek realitas tersebut disajikan. Namun kita tidak dapat menentukan makna atas realitas tersebut. Sementara itu kita tidak dapat merepresentasikan apapun tanpanya, yang…
-
Semiotika Sosial
Pengertian istilah semiotik berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu semeion, yang artinya “tanda”. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda (Eco dalam Sobur, 2001: 95). Semiotika atau ilmu yang mengkaji tentang tanda dibangun berdasarkan asumsi dan konsep yang memungkinkan untuk melakukan analisis sistem simbolik…