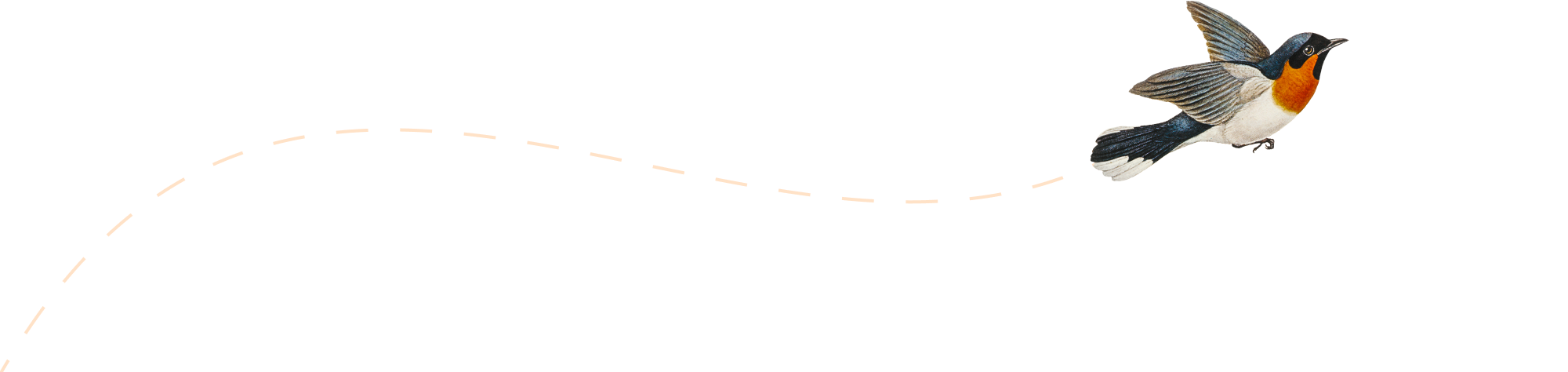-
Linguistic Aspect of Verbal Humor in Stand-up Comedy
Penelitian yang dilakukan oleh Fairza Hirji (2009), dari McMaster University Kanada, mengangkat tema tentang komedi yang didasarkan pada rasisme yang dilakukan oleh komedian Russell Peters. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan isu rasial dalam komedi. Untuk itu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana batasan wacana rasial dalam komedi. Russell Peters seringkali mengangkat isu rasial dengan menirukan…
-
Stand-up Comedy Around The World: Americanisation and the role of globalised media
Penelitian yang dilakukan oleh Juan M. Sjöbohn (2008) dari Malmö University Swedia, meneliti tentang perkembangan stand up comedy di Amerika dan Swedia dalam kaitannya dengan Amerikanisasi dan globalisasi media, serta bagaimana comic swedia menerapkan ‘tradisi’ Amerika, melalui stand up comedy di Swedia. Sjöbohn melakukan perbandingan dalam analisis konten comic Bill Hicks dari Amerika dengan Magnus…
-
A Womanist Discourse Analysis of The Comedic Discourse of Jackie “Moms” Mabley
Penelitian yang dilakukan oleh Natasha Patterson (2006) dari University of Florida, meneliti tentang wacana perempuan dalam materi-materi comic Jackie Mabley. Terdapat empat fokus penelitian yaitu: rentang representasi wacana tentang wanita kulit hitam dalam materi comic Jackie Mabley; gerakan nasionalisme kaum kulit hitam di Amerika; fungsi dari pemilihan wacana wanita kulit hitam dalam stand up comedy…
-
Stand Up Comedy: Prescious popular humour for those who literate
Abstract Stand up comedy is a show genre which presenting a comic who does speech in front of his /her audience. A humour genre which came from the west, but rapidly flourishing in Indonesia since the mid 2011. Stand up comedy, is now an indispensable part on Indonesia popular culture stigmatized as the “literate comedy”…
-
Model
Menurut Deutsch (1951) dalam Severin & Tankard, model adalah struktur simbol dan aturan kerja yang diharapkan selaras dengan serangkaian poin yang relevan dalam struktur atau proses yang ada ². Sedangkan Peter Hartley menyatakan bahwa “A model is quite simply a scaled-down representation of some thing or event” ³. Aubrey fisher menyatakan bahwa model pada…
-
Bisakah menggabungkan penelitian kualitatif dengan kuantitatif?
Bisa, Sebuah penelitian dilakukan adalah mencari jawaban yang benar dari sebuah atau beberapa pertanyaan penelitian untuk memahami fenomena. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif merupakan cara yang dirumuskan untuk memperoleh kebenaran yang benar. Dari tujuan mendasar dari sebuah penelitian, maka menggabungkan dua pendekatan, pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dalam sebuah penelitian bukanlah hal yang ‘haram’. Denzin & Lincoln…
-
Popperian falsification (Karl R. Popper)
Popper merupakan pemikir Jerman yang berkembang di lingkungan yang mendukung teori verifikasi. Namun ia menolaknya dan mengajukan metode falsifikasi. Falsifikasi adalah pengujian pengetahuan secara asimetris, dimana kebenaran teori tersebut hanya sekedar dugaan, sedangkan perkiraan kesalahan merupakan satu kepastian. Menurutnya, ilmu pengetahuan tidak hanya dihasilkan dan bekerja dengan logika induksi semata. Logika induksi adalah logika penarikan…
-
Hypothetico-deductivism (Sir Isac Newton)
Asas deducto-hipotetico verificative dianggap sebagai jalan keluar atas pertentangan antara berfikir induktif (salah satunya Bacon) dan deduktif (salah satunya Descartes). Menurut Herman Soewardi, bahwa pada abad ke-20 banyak pakar yang berpandangan bahwa sebenarnya dalam cara berfikir orang hanya terdapat satu cara berfikir yaitu deduktif, dedangkan induktif hanya merupakan deduktif yang sebaliknya. Sungguhpun demikian, sebuah penelitian…
-
Baconian inductivism (Francis Bacon) Novum Organum (1920)
Metoda induktif utuk menemukan kebenaran, disasarkan pada pengamatan empiris, analisis data yang diamati, penyimpulan yang terwujud dalam hipotesis (kesimpulan sementara), dan verifikasi hipotesisi melalui pengamatan dan eksperimen lebih lanjut. Penggunaan metoda induktif Bacon mengharuskan pencabutan hal yang hakiki dari hal yng tidak hakiki dan penemuan struktur atau bentuk yang mendasari fenomena yang sedang diteliti, dengan…
-
The Basic Structure of science
Data merupakan komponen penting bagi sebuah teori maupun ilmu. Data merupakan sekumpulan informasi atas realitas. Demikianpun setiap ilmuwan tidak akan mamapu mendapatkan informasi yang sempurna dan menyeluruh atas realitas yang diamati. Terutama dalam bidang ilmu komunikasi (sosial) yang mengkaji ‘fenomena-fenomena manusia’, dimana objek dan subjek kajian sangat dinamis sehingga setiap data akan menjadi sangat unik.…